Etika, Moral, Nilai Dan Norma
a. Pengertian Etika
Sebelum membahas lebih dalam mengenai etika, moral, nilai dan norma dalam kancah Aparatur Negara dan Pegawai Negeri Sipil perlu dibahas terlebih dahulu beberapa pengertian Etika, Moral, Nilai dan Norma.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini dimana dengan semakin derasnya arus informasi sehingga tidak ada lagi batasan antara satu negara dengan negara lainnya. Dampak ini juga sangat dirasakan dalam penerapan etika, sehingga seringkali terdengar pelanggaran hak azasi manusia dan penyalagunaan wewenang dan tanggungjawab.
Walaupun demikian dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus tetap ditegakkan nilai-nilai yang secara normatif harus tetap dijaga keberadaannya.
Istilah dan pengertian etika secara kebahasaan/etimologi, berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Biasanya etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.
Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.
Pengertian moralitas adalah pedoman yang dimiliki setiap individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral yang berlaku dalam masyarakat.
Disamping itu etika dapat disebut juga sebagai filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak, berdasarkan norma-norma tertentu.
Moralitas dipertanyakan tampak (tangible) dalam perilaku tidak jujur dan tidak tampak (intangible) dalam pikiran yang bertentangan dengan hati nurani dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Moralitas yang dengan sengaja menentang hati nurani adalah soal integritas, yaitu keteguhan hati untuk berpendirian tetap mempertahankan nilai-nilai baku.
Jadi pengertian etika dan moralitas memiliki arti yang sama sebagai sebuah sistem tata nilai tentang bagaimana manusia harus tetap mempertahankan hidup yang baik, yang kemudian terwujud dalam pola tingkah laku/perilaku yang konstan dan berulang dalam kurun waktu, yang berjalan dari waktu kewaktu sehingga menjadi suatu kebiasaan.
Berbeda lagi antara etika dengan etiket, seperti telah dibahas etika adalah berarti moral sedangkan etiket berarti sopan santun, walaupun keduanya menyangkut perilaku manusia secara normatif yaitu memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang diperbolehkan dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Pengertian etiket dan etika sering dicampuradukkan, padahal kedua istilah tersebut terdapat arti yang berbeda, walaupun ada persamaannya. Istilah etika sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan moral (mores), sedangkan kata etiket adalah berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal.
Persamaannya adalah mengenai perilaku manusia secara normatif yang etis. Artinya memberikan pedoman atau norma-norma tertentu yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan.Istilah etiket berasal dari Etiquette (Perancis) yang berarti dari awal suatu kartu undangan yang biasanya dipergunakan semasa raja-raja di Perancis mengadakan pertemuan resmi, pesta dan resepsi untuk kalangan para elite kerajaan atau bangsawan.
Pendapat lain mengatakan bahwa etiket adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah lake sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan beberapa arti dari kata “etiket”, yaitu :
1. Etiket (Belanda) secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang (dagang) yang bertuliskan nama, isi, dan sebagainya tentang barang itu.
2. Etiket (Perancis) adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik.
Beberapa perbedaan yang mendasar antara etika dan etiket :
Selain ada persamaannya, dan juga ada empat perbedaan antara etika dan etiket, yaitu secara umumnya sebagai berikut:
1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket adalah menetapkan cara, untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan.
2. Etika adalah nurani (bathiniah), bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Etiket adalah formalitas (lahiriah), tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan.
3. Etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi.Etiket bersifat relatif, yaitu yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya.
Etika berlakunya, tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etiket hanya berlaku, jika ada orang lain yang hadir, dan jika tidak ada orang lain maka etiket itu tidak berlaku.
b. Macam-macam Etika
Dalam membahas Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral (mores). Manusia disebut etis, ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika, terdapat dua macam etika (Keraf: 1991: 23), sebagai berikut:
Etika Deskriptif
Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Da-pat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.
Etika Normatif
Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.
Dari berbagai pembahasan definisi tentang etika tersebut di atas dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) jenis definisi, yaitu sebagai berikut:
· Jenis pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia.
· Jenis kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma, karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik.
· Jenis ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Definisi etika ini lebih bersifat informatif, direktif dan reflektif.
c. Fungsi Etika
Etika tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik, itu ajaran moral, melainkan etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan. Etika ingin menampilkan ketrampilan intelektual yaitu ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengabil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Pluralisme moral diperlukan karena:
· pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah budaya dan agama yang hidup berdampingan;
· modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional;
· berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup.
Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum yang berisi prinsip serta moral dasar dan etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus. Etika khusus ini masih dibagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika sosial dibagi menjadi:
(1) Sikap terhadap sesama;
(2) Etika keluarga
(3) Etika profesi misalnya etika untuk pustakawan, arsiparis, dokumentalis, pialang informasi
(4) Etika politik
(5) Etika lingkungan hidup , serta
(6) Kritik ideologi Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang ajaran moral sedangka moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dsb. Etika selalu dikaitkan dengan moral serta harus dipahami perbedaan antara etika dengan moralitas.
a. Pengertian Moral
Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata ‘moral’ yaitu mos sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata ‘etika’, maka secara etimologis, kata ’etika’ sama dengan kata ‘moral’ karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan,adat. Dengan kata lain, kalau arti kata ’moral’ sama dengan kata ‘etika’, maka rumusan arti kata ‘moral’ adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu ‘etika’ dari bahasa Yunani dan ‘moral’ dari bahasa Latin. Jadi bila kita mengatakan bahwa perbuatan pengedar narkotika itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Atau bila kita mengatakan bahwa pemerkosa itu bermoral bejat, artinya orang tersebut berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang tidak baik.
‘Moralitas’ (dari kata sifat Latin moralis) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan ‘moral’, hanya ada nada lebih abstrak. Berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.
Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematik terhadap anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban manusia.
Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai dan ajaran moral. Etika merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai 5 ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif (tidak sekadar melaporkan pandangan moral melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya).
b. Moralitas
Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat di antara sekelompok manusia. Adapun nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Norma moral adalah tentang bagaimana manusia harus hidup Supaya menjadi baik sebagai manusia. Ada perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan pada umumnya. Kebaikan moral merupakan kebaikan manusia sebagai manusia sedangkan kebaikan pada umumnya merupakan kebaikan manusia dilihat dari satu segi saja, misalnya sebagai suami atau isteri, sebagai pustakawan.
Moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adala sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau sopan santun. Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber. Etika dan moralitas Etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang mereflesikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai lima ciri khas yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif. Rasional berarti mendasarkan diri pada rasio atau nalar, pada argumentasi yang bersedia untuk dipersoalkan tanpa perkecualian. Kritis berarti filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai ke akar-akarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal. Sistematis artinya membahas langkah demi langkah. Normatif menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya. Etika dan agama
Etika tidak dapat menggantikan agama. Orang yang percaya menemukan orientasi dasar kehidupan dalam agamanya. Agama merupakan hal yang tepat untuk memberikan orientasi moral. Pemeluk agama menemukan orientasi dasar ehidupan dalam agamanya. Akan tetapi agama itu memerlukan ketrampilan etika agar dapat memberikan orientasi, bukan sekadar indoktrinasi. Hal ini disebabkan empat alasan sebagai berikut:
1. Orang agama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. Ia tidak puas mendengar bahwa Tuhan memerintahkan sesuatu, tetapu ia juga ingin mengertimengapa Tuhan memerintahkannya. Etika dapat membantu menggali rasionalitas agama.
2. Seringkali ajaran moral yang termuat dalam wahyu mengizinkan interpretasi yang saling berbeda dan bahkan bertentangan.
3. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat maka agama menghadapi masalah moral yang secara langsung tidak disinggung-singgung dalam wahyu. Misalnya bayi tabung, reproduksi manusia dengan gen yang sama.
4. Adanya perbedaan antara etika dan ajaran moral. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional semata-mata sedangkan agama pada wahyunya sendiri. Oleh karena itu ajaran agama hanya terbuka pada mereka yang mengakuinya sedangkan etika terbuka bagi setiap orang dari
a. Pengertian Nilai
Untuk memahami pengertian nilai secara lebih dalam, berikut ini akan disajikan sejumlah definisi nilai dari beberapa ahli.
“Value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence.” (Rokeach, 1973)
“Value is a general beliefs about desirable or undesireable ways of behaving and about desirable or undesireable goals or end-states.” (Feather, 1994 hal. 184)
“Value as desireable transsituatioanal goal, varying in importance, that serve as guiding principles in the life of a person or other social entity.” (Schwartz, 1994)
Lebih lanjut Schwartz (1994) juga menjelaskan bahwa nilai adalah (1) suatu keyakinan, (2) berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu, (3) melampaui situasi spesifik, (4) mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku, individu, dan kejadian-kejadian, serta (5) tersusun berdasarkan derajat kepentingannya.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terlihat kesamaan pemahaman tentang nilai, yaitu (1) suatu keyakinan, (2) berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya.
Pemahaman tentang nilai tidak terlepas dari pemahaman tentang bagaimana nilai itu terbentuk. Schwartz berpandangan bahwa nilai merupakan representasi kognitif dari tiga tipe persyaratan hidup manusia yang universal, yaitu :
1. kebutuhan individu sebagai organisme biologis;
2. persyaratan interaksi sosial yang membutuhkan koordinasi interpersonal;
3. tuntutan institusi sosial untuk mencapai kesejahteraan kelompok dan kelangsungan hidup kelompok (Schwartz & Bilsky, 1987; Schwartz, 1992, 1994).
Jadi, dalam membentuk tipologi dari nilai-nilai, Schwartz mengemukakan teori bahwa nilai berasal dari tuntutan manusia yang universal sifatnya yang direfleksikan dalam kebutuhan organisme, motif sosial (interaksi), dan tuntutan institusi sosial (Schwartz & Bilsky, 1987). Ketiga hal tersebut membawa implikasi terhadap nilai sebagai sesuatu yang diinginkan.
Schwartz menambahkan bahwa sesuatu yang diinginkan itu dapat timbul dari minat kolektif (tipe nilai benevolence, tradition, conformity) atau berdasarkan prioritas pribadi / individual (power, achievement, hedonism, stimulation, self-direction), atau kedua-duanya (universalism, security). Nilai individu biasanya mengacu pada kelompok sosial tertentu atau disosialisasikan oleh suatu kelompok dominan yang memiliki nilai tertentu (misalnya pengasuhan orang tua, agama, kelompok tempat kerja) atau melalui pengalaman pribadi yang unik (Feather, 1994; Grube, Mayton II & Ball-Rokeach, 1994; Rokeach, 1973; Schwartz, 1994).
Nilai sebagai sesuatu yang lebih diinginkan harus dibedakan dengan yang hanya ‘diinginkan’, di mana ‘lebih diinginkan’ mempengaruhi seleksi berbagai modus tingkah laku yang mungkin dilakukan individu atau mempengaruhi pemilihan tujuan akhir tingkah laku (Kluckhohn dalam Rokeach, 1973). ‘Lebih diinginkan’ ini memiliki pengaruh lebih besar dalam mengarahkan tingkah laku, dan dengan demikian maka nilai menjadi tersusun berdasarkan derajat kepentingannya.
Sebagaimana terbentuknya, nilai juga mempunyai karakteristik tertentu untuk berubah. Karena nilai diperoleh dengan cara terpisah, yaitu dihasilkan oleh pengalaman budaya, masyarakat dan pribadi yang tertuang dalam struktur psikologis individu (Danandjaja, 1985), maka nilai menjadi tahan lama dan stabil (Rokeach, 1973). Jadi nilai memiliki kecenderungan untuk menetap, walaupun masih mungkin berubah oleh hal-hal tertentu. Salah satunya adalah bila terjadi perubahan sistem nilai budaya di mana individu tersebut menetap (Danandjaja, 1985).
b. Tipe Nilai (Value Type)
Penelitian Schwartz mengenai nilai salah satunya bertujuan untuk memecahkan masalah apakah nilai-nilai yang dianut oleh manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe nilai (value type). Lalu masing-masing tipe tersebut terdiri pula dari sejumlah nilai yang lebih khusus. Setiap tipe nilai merupakan wilayah motivasi tersendiri yang berperan memotivasi seseorang dalam bertingkah laku. Karena itu, Schwartz juga menyebut tipe nilai ini sebagai motivational type of value.
Dari hasil penelitiannya di 44 negara, Schwartz (1992, 1994) mengemukakan adanya 10 tipe nilai (value types) yang dianut oleh manusia, yaitu :
1. Power. Tipe nilai ini merupakan dasar pada lebih dari satu tipe kebutuhan yang universal, yaitu transformasi kebutuhan individual akan dominasi dan kontrol yang diidentifikasi melalui analisa terhadap motif sosial. Tujuan utama dari tipe nilai ini adalah pencapaian status sosial dan prestise, serta kontrol atau dominasi terhadap orang lain atau sumberdaya tertentu. Nilai khusus (spesific values) tipe nilai ini adalah : social power, authority, wealth, preserving my public image dan social recognition.
2. Achievement. Tujuan dari tipe nilai ini adalah keberhasilan pribadi dengan menunjukkan kompetensi sesuai standar sosial. Unjuk kerja yang kompeten menjadi kebutuhan bila seseorang merasa perlu untuk mengembangkan dirinya, serta jika interaksi sosial dan institusi menuntutnya. Nilai khusus yang terdapat pada tipe nilai ini adalah : succesful, capable, ambitious, influential.
3. Hedonism. Tipe nilai ini bersumber dari kebutuhan organismik dan kenikmatan yang diasosiasikan dengan pemuasan kebutuhan tersebut. Tipe nilai ini mengutamakan kesenangan dan kepuasan untuk diri sendiri. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah : pleasure, enjoying life.
4. Stimulation. Tipe nilai ini bersumber dari kebutuhan organismik akan variasi dan rangsangan untuk menjaga agar aktivitas seseorang tetap pada tingkat yang optimal. Unsur biologis mempengaruhi variasi dari kebutuhan ini, dan ditambah pengaruh pengalaman sosial, akan menghasilkan perbedaan individual tentang pentingnya nilai ini. Tujuan motivasional dari tipe nilai ini adalah kegairahan, tantangan dalam hidup. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah : daring, varied life, exciting life.
5. Self-direction. Tujuan utama dari tipe nilai ini adalah pikiran dan tindakan yang tidak terikat (independent), seperti memilih, mencipta, menyelidiki. Self-direction bersumber dari kebutuhan organismik akan kontrol dan penguasaan (mastery), serta interaksi dari tuntutan otonomi dan ketidakterikatan. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah : creativity, curious, freedom, choosing own goals, independent.
6. Universalism. Tipe nilai ini termasuk nilai-nilai kematangan dan tindakan prososial. Tipe nilai ini mengutamakan penghargaan, toleransi, memahami orang lain, dan perlindungan terhadap kesejahteraan umat manusia. Contoh nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah : broad-minded, social justice, equality, wisdom, inner harmony.
7. Benevolence. Tipe nilai ini lebih mendekati definisi sebelumnya tentang konsep prososial. Bila prososial lebih pada kesejahteraan semua orang pada semua kondisi, tipe nilai benevolence lebih kepada orang lain yang dekat dari interaksi sehari-hari. Tipe ini dapat berasal dari dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan interaksi yang positif untuk mengembangkan kelompok, dan kebutuhan organismik akan afiliasi. Tujuan motivasional dari tipe nilai ini adalah peningkatan kesejahteraan individu yang terlibat dalam kontak personal yang intim. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah : helpful, honest, forgiving, responsible, loyal, true friendship, mature love.
8. Tradition. Kelompok dimana-mana mengembangkan simbol-simbol dan tingkah laku yang merepresentasikan pengalaman dan nasib mereka bersama. Tradisi sebagian besar diambil dari ritus agama, keyakinan, dan norma bertingkah laku. Tujuan motivasional dari tipe nilai ini adalah penghargaan, komitmen, dan penerimaan terhadap kebiasaan, tradisi, adat istiadat, atau agama. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah : humble, devout, accepting my portion in life, moderate, respect for tradition.
9. Conformity. Tujuan dari tipe nilai ini adalah pembatasan terhadap tingkah laku, dorongan-dorongan individu yang dipandang tidak sejalan dengan harapan atau norma sosial. Ini diambil dari kebutuhan individu untuk mengurangi perpecahan sosial saat interaksi dan fungsi kelompok tidak berjalan dengan baik. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah : politeness, obedient, honoring parents and elders, self discipline.
10. Security. Tujuan motivasional tipe nilai ini adalah mengutamakan keamanan, harmoni, dan stabilitas masyarakat, hubungan antar manusia, dan diri sendiri. Ini berasal dari kebutuhan dasar individu dan kelompok. Tipe nilai ini merupakan pencapaian dari dua minat, yaitu individual dan kolektif. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah : national security, social order, clean, healthy, reciprocation of favors, family security, sense of belonging.
c. Struktur Hubungan Nilai
Selain adanya 10 tipe nilai ini, Schwartz juga berpendapat bahwa terdapat suatu struktur yang menggambarkan hubungan di antara nilai-nilai tersebut. Untuk mengidentifikasi struktur hubungan antar nilai, asumsi yang dipegang adalah bahwa pencapaian suatu tipe nilai mempunyai konsekuensi psikologis, praktis, dan sosial yang dapat berkonflik atau sebaliknya berjalan seiring (compatible) dengan pencapaian tipe nilai lain. Misalnya, pencapaian nilai achievement akan berkonflik dengan pencapaian nilai benevolence, karena individu yang mengutamakan kesuksesan pribadi dapat merintangi usahanya meningkatkan kesejahteraan orang lain. Sebaliknya, pencapaian nilai benevolence dapat berjalan selaras dengan pencapaian nilai conformity karena keduanya berorientasi pada tingkah laku yang dapat diterima oleh kelompok sosial.
Pencapaian nilai yang seiring satu dengan yang lain menghasilkan sistem hubungan antar nilai sebagai berikut :
1) Tipe nilai power dan achievement, keduanya menekankan pada superioritas sosial dan harga diri
2) Tipe nilai achievement dan hedonism, keduanya menekankan pada pemuasan yang terpusat pada diri sendiri
3) Tipe nilai hedonism dan stimulation, keduanya menekankan keinginan untuk memenuhi kegairahan dalam diri
4) Tipe nilai stimulation dan self-direction, keduanya menekankan minat intrinsik dalam bidang baru atau menguasai suatu bidang
5) Tipe nilai self-direction dan universalism, keduanya mengekspresikan keyakinan terhadap keputusan atau penilaian diri dan pengakuan terhadap adanya keragaman dari hakekat kehidupan
6) Tipe nilai universalism dan benevolence, keduanya menekankan orientasi kesejahteraan orang lain dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi
7) Tipe nilai benevolence dan conformity, keduanya menekankan tingkah laku normatif yang menunjang interaksi intim antar pribadi
8) Tipe nilai benevolence dan tradition, keduanya mengutamakan pentingnya arti suatu kelompok tempat individu berada
9) Tipe nilai conformity dan tradition, keduanya menekankan pentingnya memenuhi harapan sosial di atas kepentingan diri sendiri
10) Tipe nilai tradition dan security, keduanya menekankan pentingnya aturan-aturan sosial untuk memberi kepastian dalam hidup
11) Tipe nilai conformity dan security, keduanya menekankan perlindungan terhadap aturan dan harmoni dalam hubungan sosial
12) Tipe nilai security dan power, keduanya menekankan perlunya mengatasi ancaman ketidakpastian dengan cara mengontrol hubungan antar manusia dan sumberdaya yang ada.
Berdasarkan adanya tipe nilai yang sejalan dan berkonflik, Schwartz menyimpulkan bahwa tipe nilai dapat diorganisasikan dalam dimensi bipolar, yaitu :
1) Dimensi opennes to change yang mengutamakan pikiran dan tindakan independen yang berlawanan dengan dimensi conservation yang mengutamakan batasan-batasan terhadap tingkah laku, ketaatan terhadap aturan tradisional, dan perlindungan terhadap stabilitas. Dimensi opennes to change berisi tipe nilai stimulation dan self direction, sedangkan dimensi conservation berisi tipe nilai conformity, tradition, dan security.
2) Dimensi yang kedua adalah dimensi self-transcendence yang menekankan penerimaan bahwa manusia pada hakekatnya sama dan memperjuangkan kesejahteraan sesama yang berlawanan dengan dimensi self-enhancement yang mengutamakan pencapaian sukses individual dan dominasi terhadap orang lain. Tipe nilai yang termasuk dalam dimensi self-transcendence adalah universalism dan benevolence. Sedangkan tipe nilai yang termasuk dalam dimensi self-enhancement adalah achievement dan power. Tipe nilai hedonism berkaitan baik dengan dimensi self-enhancement maupun openness to change
Hubungan Nilai Dan Tingkah Laku
Di dalam kehidupan manusia, nilai berperan sebagai standar yang mengarahkan tingkah laku. Nilai membimbing individu untuk memasuki suatu situasi dan bagaimana individu bertingkah laku dalam situasi tersebut (Rokeach, 1973; Kahle dalam Homer & Kahle, 1988). Nilai menjadi kriteria yang dipegang oleh individu dalam memilih dan memutuskan sesuatu (Williams dalam Homer & Kahle, 1988). Danandjaja (1985) mengemukakan bahwa nilai memberi arah pada sikap, keyakinan dan tingkah laku seseorang, serta memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan pada setiap individu. Karenanya nilai berpengaruh pada tingkah laku sebagai dampak dari pembentukan sikap dan keyakinan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai merupakan faktor penentu dalam berbagai tingkah laku sosial (Rokeach, 1973; Danandjaja, 1985).
Mengacu pada BST, nilai merupakan salah satu komponen yang berperan dalam tingkah laku : perubahan nilai dapat mengarahkan terjadinya perubahan tingkah laku. Hal ini telah dibuktikan dalam sejumlah penelitian yang berhasil memodifikasi tingkah laku dengan cara mengubah sistem nilai (Grube dkk., 1994; Sweeting, 1990; Waller, 1994; Greenstein, 1976; Grube, Greenstein, Rankin & Kearney, 1977; Schwartz & Inbar-Saban, 1988).
d. Fungsi Nilai
Fungsi utama dari nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai sebagai standar (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992, 1994), fungsinya ialah:
· Membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam social issues tertentu (Feather, 1994).
· Mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik yang lain.
· Mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain.
· Melakukan evaluasi dan membuat keputusan.
· Mengarahkan tampilan tingkah laku membujuk dan mempengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan, sikap, nilai dan tingkah laku individu lain yang berbeda, yang bisa diprotes dan dibantah, bisa dipengaruhi dan diubah.
2) Sistim nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan (Feather, 1995; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992, 1994). Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktivasi beberapa nilai dalam sistim nilai individu. Umumnya nilai-nilai yang teraktivasi adalah nilai-nilai yang dominan pada individu yang bersangkutan.
3) Fungsimotivasional. Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional. Nilai dapat memotivisir individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu (Rokeach, 1973; Schwartz, 1994), memberi arah dan intensitas emosional tertentu terhadap tingkah laku (Schwartz, 1994). Hal ini didasari oleh teori yang menyatakan bahwa nilai juga merepresentasikan kebutuhan (termasuk secara biologis) dan keinginan, selain tuntutan sosial (Feather, 1994; Grube dkk., 1994).
Nilai Sebagai Keyakinan (Belief)
Dari definisinya, nilai adalah keyakinan (Rokeach, 1973; Schwartz, 1994; Feather, 1994) sehingga pembahasan nilai sebagai keyakinan perlu untuk memahami keseluruhan teori nilai, terutama keterkaitannya dengan tingkah laku. Nilai itu sendiri merupakan keyakinan yang tergolong preskriptif atau proskriptif, yaitu beberapa cara atau akhir tindakan dinilai sebagai diinginkan atau tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan definisi dari Allport bahwa nilai adalah suatu keyakinan yang melandasi seseorang untuk bertindak berdasarkan pilihannya (dalam Rokeach, 1973). Robinson dkk. (1991) mengemukakan bahwa keyakinan, dalam konsep Rokeach, bukan hanya pemahaman dalam suatu skema konseptual, tapi juga predisposisi untuk bertingkah laku yang sesuai dengan perasaan terhadap obyek dari keyakinan tersebut.
Dalam Rokeach (1973) dikatakan, sebagai keyakinan, nilai memiliki aspek kognitif, afektif dan tingkah laku dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Nilai meliputi kognisi tentang apa yang diinginkan, menjelaskan pengetahuan, opini dan pemikiran individu tentang apa yang diinginkan.
2) Nilai meliputi afektif, di mana individu atau kelompok memiliki emosi terhadap apa yang diinginkan, sehingga nilai menjelaskan perasaan individu atau kelompok terhadap apa yang diinginkan itu.
3) Nilai memiliki komponen tingkah laku, artinya nilai merupakan variabel yang berpengaruh dalam mengarahkan tingkah laku yang ditampilkan.
Pemahaman nilai sebagai keyakinan, tidak dapat dipisahkan dari model yang dikembangkan Rokeach pertama kali pada tahun 1968, yang disebut Belief System Theory (BST). Grube dkk. (1994) menjelaskan bahwa BST adalah organisasi dari teori yang menjelaskan dan mengerti bagaimana keyakinan dan tingkah laku saling berhubungan, serta dalam kondisi apa sistem keyakinan dapat dipertahankan atau diubah. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam BST, tingkah laku merupakan fungsi dari sikap, nilai dan konsep diri.
Menurut Grube, Mayton, II & Rokeach (1994), BST merupakan suatu kerangka berpikir yang berupaya menjelaskan adanya organisasi antara sikap (attitude), nilai (value), dan tingkah laku (behavior). Menurut teori ini, keyakinan dan tingkah laku saling berkaitan. Keyakinan-keyakinan yang dimiliki individu terorganisasi dalam suatu dimensi sentralitas atau dimensi derajat kepentingan. Suatu keyakinan yang lebih sentral akan memiliki implikasi dan konsekuensi yang besar terhadap keyakinan lain. Jadi perubahan suatu keyakinan yang lebih sentral akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap tingkah laku dibandingkan pada keyakinan-keyakinan lain yang lebih rendah sentralitasnya. Urutan keyakinan menurut derajat sentralitasnya adalah self-conceptions, value, dan attitude.
Sikap (attitude) adalah keyakinan yang menempati posisi periferal/tepi atau paling rendah sentralitasnya dalam BST. Sikap merupakan suatu organisasi dari keyakinan-keyakinan sehari-hari tentang obyek atau situasi. Jumlah sikap yang dimiliki individu dapat berhubungan dengan banyak obyek atau situasi yang berbeda-beda. Karenanya seseorang dapat memiliki sikap yang ribuan jumlahnya. Mengingat sikap adalah keyakinan yang periferal, maka perubahan sikap hanya memiliki pengaruh yang terbatas pada tingkah laku.
Nilai (value) adalah keyakinan berikutnya yang lebih sentral. Nilai melampaui suatu obyek dan situasi tertentu. Nilai memegang peranan penting karena merupakan representasi kognitif dari kebutuhan individu di satu sisi dan tuntutan sosial di sisi lain.
Konsep diri (self-conceptions) adalah keyakinan sentral dari BST. Menurut Rokeach (dalam Grube, Mayton, II & Rokeach, 1994) konsep diri adalah keseluruhan konsepsi individu tentang dirinya yang meliputi organisasi semua kognisi dan konotasi afektif yang berupaya menjawab pertanyaan "Siapa diri saya ini?". Semua keyakinan lain dan tingkah laku terorganisasi di sekeliling konsep diri dan berupaya menjaga konsep diri yang positif.
Jadi, perubahan pada satu komponen BST, akan menyebabkan perubahan pada komponen lain termasuk tingkah laku. Berbeda dengan sikap, nilai adalah keyakinan tunggal yang mengatasi obyek maupun situasi. Karenanya, perubahan nilai lebih dimungkinkan akan menyebabkan perubahan komponen lainnya dibandingkan yang lain.
Pengukuran Nilai
Selama ini pengukuran nilai didasarkan kepada hasil evaluasi diri yang dilaporkan oleh individu ke dalam suatu skala pengukuran (mis. Rokeach value survey, Schwartz value survey). Evaluasi diri membutuhkan pemahaman kognitif maupun afektif terhadap diri sendiri, termasuk untuk membedakan antara nilai ideal normatif dan nilai faktual yang ada saat ini. Sejalan dengan hal ini, Schwartz, Verkasalo, Antonovsky dan Sagiv (1997) melihat hubungan antara respon terhadap social desirability dan skala nilai berdasarkan pelaporan diri. Mereka membuktikan bahwa terjadi bias pada pengukuran nilai yang mengandung aspek social desirability tinggi, yaitu pada tipe nilai hedonism, stimulation, self-direction, achievement dan power. Jadi pengukuran nilai yang menggunakan skala pelaporan diri pada penelitian yang banyak dipengaruhi aspek social desirability seperti dalam penelitian ini (mis. t
Cara lain yang digunakan untuk mengetahui nilai individu adalah dengan teknik wawancara. Teknik ini telah digunakan oleh Rokeach (1973) untuk menggali nilai-nilai apa saja yang dimiliki seseorang. Ia melakukan wawancara dengan para responden yang dimintanya untuk menjawab pertanyaan tentang nilai apa yang menjadi tujuan akhir mereka.
Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, nilai-nilai seseorang akan tampak dalam beberapa indikator :
1) Berkaitan dengan definisi nilai sebagai cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu, maka indikator pertama adalah pernyataan tentang keinginan-keinginan, prinsip hidup dan tujuan hidup seseorang.
2) Indikator berikutnya adalah tingkah laku subyek dalam kehidupannya sehari-hari. Nilai berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bertingkah laku, memberi arah pada tingkah laku dan memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan. Jadi tingkah laku seseorang mencerminkan nilai-nilai yang dianutnya. Dari tingkah laku dapat dilihat apa yang menjadi prioritasnya, apa yang lebih diinginkan oleh seseorang.
3) Fungsi nilai adalah memotivasi tingkah laku. Seberapa besar seseorang berusaha mencapai apa yang diinginkannya dan intensitas emosional yang diatribusikan terhadap usahanya tersebut, dapat menjadi ukuran tentang kekuatan nilai yang dianutnya.
4) Salah satu fungsi dari nilai adalah dalam memecahkan konflik dan mengambil keputusan. Dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengambil keputusan dari situasi yang menimbulkan konflik, nilainya yang dominan akan teraktivasi. Jadi, apa keputusan seseorang dalam situasi konflik tersebut dapat dijadikan indikator tentang nilai yang dianutnya.
5) Fungsi lain dari nilai adalah membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam suatu topik sosial tertentu dan mengevaluasinya. Jadi apa pendapat seseorang tentang suatu topik tertentu dan bagaimana ia mengevaluasi topik tersebut, dapat menggambarkan nilai-nilainya.
a. Pengertian Norma
Di dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal dengan istilah norma-norma atau kaidah, yaitu biasanya suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Patokan atau pedoman tersebut sebagai norma (norm) atau kaidah yang merupakan standar yang harus ditaati atau dipatuhi (Soekanto: 1989:7).
Kehidupan masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran yang beraneka ragam, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri, akan tetapi kepentingan bersama itu mengharuskan adanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peraturan yang disepakati bersama, yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat, yang disebut peraturan hidup.Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan dengan aman, tertib dan damai tanpa gangguan tersebut, maka diperlukan suatu tata (orde=ordnung), dan tata itu diwujudkan dalam “aturan main” yang menjadi pedoman bagi segala pergaulan kehidupan sehari-hari, sehingga kepentingan masing-masing anggota masyarakat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui “hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tata peraturan”, dan tata itu lazim disebut “kaedah” (bahasa Arab), dan “norma” (bahasa Latin) atau ukuran-ukuran yang menjadi pedoman, norma-norma tersebut mempunyai dua macam menurut isinya, yaitu:
1. Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik.
2. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang tidak baik.Artinya norma adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang hams bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankannya, dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari (Kansil, 1989:81).
Norma-norma itu dapat dipertahankan melalui sanksi-sanksi, yaitu berupa ancaman hukuman terhadap siapa yang telah melanggarnya.
Tetapi dalam kehidupan masyarakat yang terikat oleh peraturan hidup yang disebut norma, tanpa atau dikenakan sanksi atas pelanggaran, bila seseorang melanggar suatu norma, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan sifatnya suatu pelanggaran yang terjadi, misalnya sebagai berikut:
- Mengangkat gagang telepon setelah di ujung bunyi ke tiga kalinya serta mengucapkan salam, dan jika mengangkat telepon sedang berdering dengan kasar, maka sanksinya dianggap “intrupsi” adalah menunjukkan ketidaksenangan yang tidak sopan dan tidak menghormati si penelepon atau orang yang ada disekitarnya.
- Orang yang mencuri barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka sanksinya cukup berat dan bersangkutan dikenakan sanksi hukuman, baik hukuman pidana penjara maupun perdata (ganti rugi).
Kemudian norma tersebut dalam pergaulan hidup terdapat empat (4) kaedah atau norma, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum . Dalam pelaksanaannya, terbagi lagi menjadi norma-norma umum (non hukum) dan norma hukum, pemberlakuan norma-norma itu dalam aspek kehidupan dapat digolongkan ke dalam dua macam kaidah, sebagai berikut:
1. Aspek kehidupan pribadi (individual) meliputi:
Kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan yang beriman.
Kehidupan kesusilaan, nilai moral, dan etika yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi demi tercapainya kesucian hati nu-rani yang berakhlak berbudi luhur (akhlakul kharimah).
2. Aspek kehidupan antar pribadi (bermasyarakat) meliputi:
Kaidah atau norma-norma sopan-santun, tata krama dan etiketdalam pergaulan sehari-hari dalam bermasyarakat (pleasantliving together).
Kaidah-kaidah hukum yang tertuju kepada terciptanya ketertiban, kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang penuh dengan kepastian atau ketenteraman (peaceful living together).Sedangkan masalah norma non hukum adalah masalah yang cukup penting dan selanjutnya akan dibahas secara lebih luas mengenai kode perilaku dan kode profesi Humas/PR, yaitu seperti nilai-nilai moral, etika, etis, etiket, tata krama dalam pergaulan sosial atau bermasyarakat, sebagai nilai aturan yang telah disepakati bersama, dihormati, wajib dipatuhi dan ditaati.
Norma moral tersebut tidak akan dipakai untuk menilai seorang dokter ketika mengobati pasiennya, atau dosen dalam menyampaikan materi kuliah terhadap para mahasiswanya, melainkan untuk menilai bagaimana sebagai profesional tersebut menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai manusia yang berbudi luhur, juiur, bermoral, penuh integritas dan bertanggung jawab.Terlepas dari mereka sebagai profesional tersebut jitu atau tidak dalam memberikan obat sebagai penyembuhnya, atau metodologi dan keterampilan dalam memberikan bahan kuliah dengan tepat. Dalam hal ini yang ditekankan adalah “sikap atau perilaku” mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai profesional yang diembannya untuk saling menghargai sesama atau kehidupan manusia.
Pada akhirnya nilai moral, etika, kode perilaku dan kode etik standard profesi adalah memberikan jalan, pedoman, tolok ukur dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi atau keahliannya masing-masing. Pengambilan keputusan etis atau etik, merupakan aspek kompetensi dari perilaku moral sebagai seorang profesional yang telah memperhitungkan konsekuensinya, secara matang baik-buruknya akibat yang ditimbulkan dari tindakannya itu secara obyektif, dan sekaligus memiliki tanggung jawab atau integritas yang tinggi. Kode etik profesi dibentuk dan disepakati oleh para profesional tersebut bukanlah ditujukan untuk melindungi kepentingan individual (subyektif), tetapi lebih ditekankan kepada kepentingan yang lebih luas (obyektif).

.jpg)

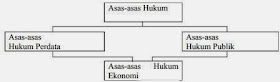
.jpg)